TEOLOGI ABSENSIA
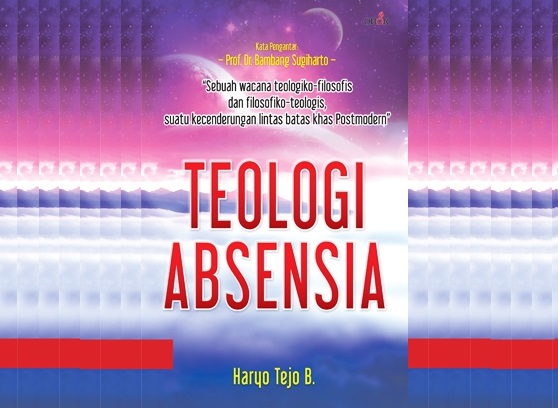
Bagaimanakah kita mesti memikirkan dan membahasakan Tuhan? Pada bulan Oktober 2013 terbit sebuah buku yang bertajuk “Teologi Absensia: Sebuah Wacana Teologiko-Filosofis dan Filosofiko-Teologis, Suatu Kecenderungan Lintas Batas Khas Postmodern” (Jakarta: OBOR). Penulisnya: Haryo Tejo B, seorang biarawan OSC, pengajar di Fakultas FIlsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Apa isi buku tersebut? Dalam salah satu bagian dari buku tersebut Haryo Tejo B sendiri menjelaskan:
“Tulisan ini hanyalah sebuah tawaran untuk berteologi. Paradigma yang coba dilarungkan penulis dalam keseluruhan buku ini adalah sebuah prolegomena akan adanya suatu alternatif wacana yang dapat –meminjam perkataan Gunawan Mohamad— mengguncang-guncang, menjebol batas, menemui malam, memasuki sebuah gelora yang merangsang karena kita dapat senantiasa dikejutkan oleh tendensinya; buku ini hanyalah sebuah isbat kepada hidup, dengan segala rindu yang tak sampai, rumah yang tak pernah tegak, petaka yang tak pernah putus, untuk meneriakkan apa yang seharusnya diteriakkan teologi: Amor Dei—kita menerima Allah dengan semacam rasa cinta. Tanpa miris, bahkan dengan gairah, karena Allah adalah cinta, Allah adalah sumber dari segala gairah. Itulah Allah yang memanggil dan mengundang dalam dan melalui Teologi Absensia (Theology of Absence).” (h. 168)
Tetapi dimana meletak pentingnya segala penjelajahan penalaran dalam buku tersebut dan apa manfaat yang dapat kita petik sebagai pembacanya? Mengenai buku itu, dalam bagian “Pengantar”, I Bambang Sugiharto dengan sedikit panjang lebar memaparkan:
“Berbagai kekerasan dan persoalan yang ditimbulkan oleh dunia agama akhir-akhir ini sebagiannya berakar pada imaji tentang Tuhan yang dibentuk oleh tradisi agama-agama. Imaji yang memang sering kali keras dan menakutkan: Tuhan adalah sosok yang senantiasa mengawasi dengan jeli, dan pada akhirnya bertindak sebagai hakim yang mengadili, dengan ancaman neraka atau imbalan surga. Kerangka berpikir di balik spiritualitas macam ini sangatlah steril hitam-putih: baik-buruk, dosa-suci, malaikat-setan, boleh-tidak boleh, dsb. Imaji dan spiritualitas macam inilah yang membuat orang beriman lantas juga berkecenderungan keras dan memandang realitas secara hitam-putih tanpa kompromi. Persoalannya sesederhana yang umumnya terjadi dalam keluarga-keluarga: bila orangtua bersikap keras dan mudah menilai perbuatan anak-anaknya secara hitam-putih tak mengenal kompromi, anak-anak itu pun akan tumbuh menjadi keras dan serba hitam-putih, tak mampu melihat kompleksitas kehidupan yang selalu penuh nuansa, penuh kontradiksi dan sering kali tumpang tindih.
Benar, imaji Tuhan dan pola spiritualitas macam itu demikian umum dan telah demikian mengakar berabad-abad lamanya. Akan tetapi, juga benar bahwa berabad-abad lamanya manusia pun telah terus-menerus mempersoalkan hal itu. Orang-orang beriman paling mumpuni yang telah mencapai puncak-puncak kesadaran religius dari tradisi agama mana pun umumnya mengritik dan menolak imaji Tuhan macam itu, bahkan menolak segala jenis pemastian ataupun pemutlakan konsep tentang Tuhan. Pada tingkat tertinggi kesadaran religius –yang biasa disebut tingkat “mistik”— bukan hanya segala predikat tentang Tuhan direlatifkan, tetapi juga urusan surga-neraka, segala bentuk hitungan angka (Tuhan itu satu atau tujuh), bahkan nama yang kita gunakan untuk menyebut-Nya pun (“Tuhan”, “Allah”, “God”, “Dieu”, dsb) ditolak dan dianggap pemberhalaan.
Sebabnya sederhana: kalau Tuhan adalah pencipta segalanya, maka Ia pasti mencakup segalanya sekaligus melebihi semuanya. Artinya tak ada kata, konsep dan angka apa pun dalam dunia manusia yang sungguh memadai untuk menyebut siapa Dia. Memastikan dan memutlakkan kata-kata, konsep dan angka tentang Tuhan hanya akan jatuh menjadi ‘pemberhalaan’. Dalam segala keterbatasan bahasa, kalau pun kita terpaksa menyebut dan memperkatakan-Nya, paling kita harus cukup puas dengan bermacam-macam metafora atau rumusan-rumusan serba kontradiktif seperti: Ia adalah ‘ada’ sekaligus ‘tiada’; kepenuhan yang kosong, kekosongan yang penuh, bagai langit; maha tunggal sekaligus tujuh atau seribu, mungkin lebih tepat tak terbilang (sistem angka adalah buatan manusia juga); dst. Para tokoh seperti Pseudo-Dionysius, John Scotus Erigena, Meister Eckhart, Jallaludin Rumi, Al Halaj, Rabiah Al Adawiyah, tetapi juga para mistikus Hindu, Buddha, Zen ataupun Taoisme, mereka semuanya umumnya sampai pada pemahaman-pemahaman “negatif” alias “apopatik” yang serupa: bahwa pada tingkat terdasar Tuhan bukanlah ini ataupun itu. Artinya, Ia lebih dari apa pun yang bisa kita bayangkan dan lukiskan. “Teologi Negativa”, begitulah istilah klasiknya.
Dari sudut ini, masalahnya lantas bukan lagi mana yang benar mana yang salah, bukan soal benar atau salah, melainkan mendalam atau dangkal. Artinya, sering kali sumber persoalan yang timbul dalam hidup beragama adalah karena kedangkalan pemahaman. Dan kedangkalan bila berpadu dengan gelegak antusiasme keagamaan memang bisa menjadi destruktif dan mengerikan. Kekerasan lantas dianggap sebagai kesalehan, kenaifan dianggap kesetiaan, membela agama secara agresif dihayati sebagai kepahlawanan. Alhasil, kehidupan beragama menjadi tampak bagai kekonyolan yang menjengkelkan. Kecenderungan ini bukan hanya destruktif bagi pihak di luar agama tersebut, tetapi terutama berbahaya dan merusak agama itu sendiri juga. Sebab, dengan cara itu agama-agama tersebut justru akan makin kehilangan esensi, integritas, dan martabatnya.
Kenaifan dan aneka kedangkalan itulah yang menyebabkan para intelektual modern hingga saat ini menjadi begitu alergi terhadap agama. Tak heran bila kaum ateis ilmiah kontemporer macam Dawkins, Sam Harris, Hitchens atau Dennet, menganggap agama semacam virus yang berbahaya. Bagi mereka agama adalah “sumber kejahatan mutlak yang meracuni segalanya” (Sam Harris) atau “gejala sakit jiwa kolektif” (Dawkins). Namun, di sisi lain pandangan macam ini pun sebenarnya merupakan kenaifan dan kedangkalan tersendiri. Sebab sebenarnya segala pretensi kepastian objektif empiris dalam dunia empiris ilmiah juga telah mendapat begitu banyak kritik mendasar dari para saintis dan filsuf ilmu itu sendiri, tidak semeyakinkan yang dikira oleh kaum ateis ilmiah itu. Perkembangan dunia ilmiah yang lebih luas pun kini sebenarnya sampai pada persoalan-persoalan mendasar yang sebenarnya telah lama direnungi dunia agama secara mendalam dan kaya, yaitu soal dimensi ruh, kesadaran, hati dan inteligensi kosmik. Pada titik itu banyak ilmuwan yang serius justru merasa perlu berdialog dengan pengalaman di dunia agama. Tengoklah riset-riset mendasar dari Francisco Varela, Ramachandran, Fritjof Capra atau Ken Wilber misalnya.
Sebaliknya, dunia agama pun tak seluruhnya naïf dan dangkal seperti yang ditudingkan kaum ateis ilmiah di atas. Tradisi besar agama-agama sesungguhnya telah selalu menggumuli aneka dilemma yang mereka hadapi, di antaranya dilemma antara kebutuhan akan kepastian normatif institusional dan kebutuhan untuk memahami misteri ilahi yang lebih tinggi; tegangan antara dogma dan pengalaman, antara tuntutan sosial duniawi horizontal dan tuntutan transendensi vertikal. Pergumulan ini telah melahirkan banyak perenungan panjang, mendalam dan bahkan radikal sejak berabad-abad yang lalu. Salah satu contoh tentang ini yang belum terlalu lama misalnya adalah mazhab “Teologi Radikal” tahun 60-an yang dipelopori Thomas Altizer, Paul van Buren, dan William Hamilton. Dalam teologi kristiani mereka ini konsep “Tuhan” malah dilepaskan sama sekali, dan sebagai gantinya, Yesus dilihat semata-mata sebagai sosok pembebas yang mendefinisikan dan mengamalkan secara canggih apa arti ideal menjadi manusia. Itu saja. Maka mereka pun nekad mencanangkan “kristianitas tanpa Tuhan dan tanpa agama”.
Sedang dalam situasi postmodern millennium ketiga ini pembicaraan tentang dimensi apopatik atau negatif konsep “Tuhan” pun sebenarnya masih berlanjut terus. Bahkan, kali ini justru wilayah filsafat sekuler yang banyak memperbincangkannya; wilayah yang di abad ke-19-an justru sangat akrab dengan ateisme. Filsuf Derrida misalnya, menekankan bahwa penyangkalan total dan final atas Tuhan sama kelirunya dengan segala pemastian teologis. Dalam hal ini ateis maupun teis sama-sama mengandung bahaya. Selalu ada kemungkinan bahwa “Tuhan” itu berbeda dari yang bisa dan biasa kita kira. Pengikut Derrida, Gianni Vattimo, menunjukkan bahwa pada kenyataannya agama adalah tradisi-tradisi yang terus-menerus menafsir ulang atau men”dekonstruksi”, teks-teks sucinya. Agama telah terus-menerus menghindar dari tendensi pemutlakan dan pemastian juga, dan sepanjang tradisinya selalu saja ada mekanisme untuk memelihara kerendahan hati dan pengakuan atas lemahnya pikiran (il pensiero debole), katanya.
Buku “Teologi Absensia” karya Haryo tejo ini adalah upaya penalaran lebih lanjut atas semua dilemma di atas dalam konteks postmodern. Selain menggamit kembali perdebatan klasik seputar “Teologi Negativa”, ia pun mencoba merumuskan kembali apa sebenarnya “teologi” itu, dan dalam situasi postmodern yang serba dekonstruktif serba tak pasti ini bagaimanakah sebaiknya kita memandang sang kebenaran ilahi itu, juga bagaimana kita mesti mendudukkan posisi agama di sana.
Meski di bidang filsafat, wacana postmodern telah banyak diterbitkan, di bidang teologi interaksi antara wacana filosofis postmodern dengan teologi masih amat langka padahal sangatlah krusial dan penting untuk merevitalisasi teologi itu sendiri hari ini. Sebagai konsekuensinya, memang wacana macam ini menjadi wacana hibrida: ia adalah wacana teologiko-filosofis, ataupun filosofiko-teologis, kecenderungan lintas batas khas postmodern. Dalam karyanya ini Haryo Tejo menawarkan sesuatu yang menarik sebagai jalan keluar dari aneka dilemma mutakhir. Silahkan menikmatinya.” (h. xi-xvi)
Bagi mereka yang ingin terus merawat hidup iman dan keagamaannya, buku ini tampaknya merupakan salah satu sosok rekan dialog yang pantas dipertimbangkan untuk dibaca dengan seksama. Dengannya barangkali kita bisa menjumpai dan menyapu debu-karat penghayatan kita dalam menjalin relasi yang indah, benar dan baik dengan Allah yang kita kasihi yang adalah Sang Kebenaran itu. (*/dack)
6,649 total views, 6 views today

Ketua Komsos Paroki St Ignatius Loyola Semplak Bogor Periode 2019-2022
